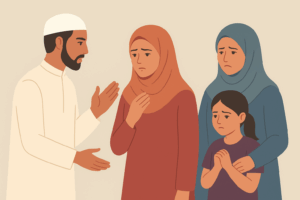Menimbang Ulang Poligami: Dari Teks ke Realitas
Oleh: Raitam Afandi
Poligami sering disebut sebagai bagian dari hukum Islam yang sah. Tapi sah secara hukum belum tentu adil secara sosial. Dalam praktiknya, poligami lebih sering menjadi ruang ketimpangan daripada ruang keadilan.
Mungkin, kita bisa bicara teks, bisa bicara dalil, tapi pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana praktik itu berdampak pada kehidupan nyata—terutama pada perempuan dan anak-anak.
Dalam konteks masyarakat kita, poligami bukan sekadar pilihan individu. Ia adalah produk dari konstruksi sosial, tafsir keagamaan, dan relasi kuasa yang tidak seimbang. Ketika laki-laki diberi ruang untuk menikah lebih dari satu, sementara perempuan dibatasi oleh norma dan stigma, maka pertanyaan tentang keadilan menjadi sangat relevan.
Poligami dalam Teks dan Tafsir
Secara tekstual, ayat yang sering dijadikan landasan poligami adalah QS An-Nisa: 3. Ayat ini muncul dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim dan perempuan pasca perang.
Poligami saat itu bukan soal hasrat, tapi soal tanggung jawab sosial. Namun, dalam praktik modern, konteks ini sering diabaikan. Yang tersisa hanya izin untuk menikah lebih dari satu, tanpa mempertimbangkan syarat utama: keadilan.
Padahal, dalam ayat yang sama, Allah juga memberi peringatan: “Jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja.” Ini bukan sekadar syarat teknis, tapi peringatan etis. Karena keadilan bukan sesuatu yang mudah dicapai, apalagi dalam relasi yang melibatkan emosi, waktu, perhatian, dan hak-hak yang kompleks.
Bahkan, sering kali keadilan dalam poligami dipersempit menjadi pembagian materi atau giliran malam. Padahal, keadilan yang dimaksud jauh lebih luas. Ia mencakup perasaan, kenyamanan psikologis, dan relasi yang setara.
Karena, bagaimana mungkin seorang suami bisa membagi cinta secara adil? Bagaimana mungkin seorang istri bisa merasa aman ketika harus berbagi pasangan hidup?
Dalam banyak kasus, poligami justru melahirkan luka. Istri pertama merasa tersisih, anak-anak bingung dengan dinamika keluarga, dan perempuan kedua sering kali menjadi objek dalam relasi kuasa.
Bahkan ketika semua pihak “mengizinkan,” itu belum tentu berarti semua pihak “rela.” Ada tekanan, ada kompromi, dan ada rasa yang tak terucapkan.
Poligami dan Relasi Kuasa
Poligami tidak bisa dilepaskan dari struktur patriarki. Dalam masyarakat yang masih menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama, poligami menjadi alat untuk memperkuat dominasi.
Bahkan, perempuan sering kali tidak punya ruang untuk menolak, apalagi untuk menentukan arah relasi. Bahkan ketika hukum memberi ruang untuk mengajukan syarat atau keberatan, secara sosial perempuan tetap dibungkam oleh stigma dan norma.
Dalam banyak kasus, perempuan yang menolak poligami dianggap tidak taat, tidak ikhlas, atau bahkan melawan agama. Padahal, menolak ketidakadilan adalah bagian dari iman.
Islam sendiri tidak pernah mengajarkan kepatuhan yang membungkam suara hati. Justru Islam mengajarkan bahwa keadilan adalah inti dari seluruh ajaran.
Dampak Poligami
Dampak poligami pada perempuan sangat kompleks. Secara psikologis, banyak perempuan yang mengalami tekanan, kecemasan, dan rasa tidak aman.
Secara sosial, mereka sering kali dikucilkan atau dianggap gagal menjaga rumah tangga. Secara hukum, mereka tidak selalu punya perlindungan yang cukup—terutama jika suami tidak berlaku adil atau tidak mencatat pernikahan kedua secara resmi.
Dalam banyak kasus, perempuan harus menanggung beban ganda: menjaga anak, mempertahankan rumah tangga, dan menghadapi stigma.
Sementara laki-laki bisa berpindah dari satu rumah ke rumah lain, perempuan harus tetap bertahan dalam ketidakpastian. Ini bukan soal cinta, tapi soal struktur yang tidak adil.
Oleh karena itu, poligami bukan sekadar soal boleh atau tidak. Ia adalah soal etika, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam konteks hari ini, ketika perempuan sudah punya kesadaran, pendidikan, dan hak yang lebih luas, maka praktik poligami harus dikaji ulang. Bukan untuk menghapus teks, tapi untuk menyesuaikan tafsir dengan realitas.
Islam adalah agama yang hidup, yang selalu relevan dengan zaman. Maka, tafsir pun harus berkembang. Kita tidak bisa terus-menerus mempertahankan praktik yang melahirkan ketidakadilan, hanya karena merasa itu bagian dari tradisi. Justru tradisi harus dikritisi, agar ajaran Islam tetap menjadi sumber rahmat dan keadilan.