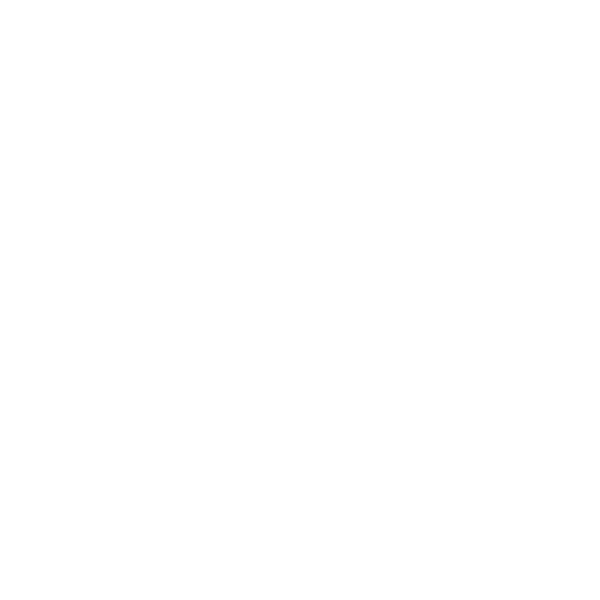Oleh Wakhit Hasim
Pengantar
Robert Chambers memiliki pemikiran unik dan penting dalam upaya perubahan sosial yang menjadi tujuan dakwah. Pemikiran ini meliputi asumsi perubahan sosial, pengenalan bias yang dibawa oleh orang luar yang mengabdi atau da’i, upaya pembalikan sudut pandang dan cara pandang pengabdi atau da’i, dan terakhir adalah asumsi tentang watak manusia.

Keempat aspek inti pemikiran Chambers ini sangat sesuai dengan watak pengabdian dalam Islam atau yang dikenal dengan istilah Dakwah. Pengabdian masyarakat menurut konsep Islam selalu berorientasi perubahan, baik individu maupun masyarakat. Perubahan Individu selalu menjadi konsen pendidikan Islam, sedangkan perubahan sosial selalu menjadi konsen dari dakwah. In terlihat pada semangat hadits Nabi “man roa minkum munkaron falyughoyir biyadihi…. ila akhirihi…“.
Watak manusia yang memiliki naluri serakah, sekaligus memiliki naluri kasih sayang juga selaras dengan filosofi manusia dalam Islam. Islam mengenal nafs dan ruh. Nafs merupakan kencederungan dalam diri yang bersifat kebinatangan pada mulanya, namun juga bisa bersifat kasih sayang, sedikit mirip dengan konsep id dalam tradisi Freudian. Ruh selain memiliki potensi internal (yang tidak dikenal oleh tradisi Freudian) seperti dalam tradisi Ibn Araby dan Plato, yang dalam proses intuisinya melibatkan faktor eksternal dan akal, melibatkan proses sosial, reasoning, namun juga keterbukaan (kasyaf/fenomenologis). Sedangkan ‘aql bersifat mempertimbangkan antara ruh dan nafs. Kesemuanya merupakan dialektika menjadi manusia sempurna, insan kamil.
Bagaimana pemikiran Chambers terkait perubahan sosial yang sesuai dengan orientasi dakwah tersebut dipaparkan di bawah ini.
Orientasi Perubahan Sosial.
Pemikiran Robert Chamber mengenai bagaimana pendekatan mengubah kenyataan masyarakat punya dua asumsi: pertama kemiskinan, ketidakberdayaan, peminggiran, kelemahan merupakan penyakit yang menjebak masyarakat untuk terus menjadi miskin dan lemah. Kedua, setiap orang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan mengubah nasipnya sendiri.

Dua asumsi ini diterapkan saat aktifis atau organizer melakukan pengorganisasian masyarakat. Tujuan pengorganisasian adalah transformasi sosial, caranya adalah memampukan masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Organizer menghadapi kenyataan posisi relasi antara orang luar dan masyarakat tempat mereka melakukan kegiatan pemberdayaan. Orang luar punya dua tipologi yaitu peneliti dan praktisi. Peneliti lazimnya bersikap negatif terhadap kemiskinan dengan bertumpu pada kajian atas sebab-sebab kemiskinan. Sedangkan praktisi akan bersikap positif optimis, karena fokus pada penyelesaian masalah.
Mengenali bias-bias dan mengubah sudut pandang pengabdi/organizer
Baik peneliti maupun praktisi membawa bias-bias saat bekerja di masyarakat yang dapat membuat mereka tidak memahami masalah masyarakat. Bias itu dapat berupa bias program, bias tempat, bias kelompok sosial, bias profesi, dan bias-bias lainnya. Bias-bias ini akan menempatkan masyarakat sebagai obyek pasif dan orang luar menjadi peneliti dan subyek penentu cara penyelesaian masalah di desa. Jika situasinya seperti ini, maka yang harus dilakukan oleh pengabdi atau aktifis adalah membalikkan cara pandang (reversal).

Metode pembalikan dilakukan secara partisipatif. Jika semula orang luar menentukan masalah, maka harus diubah masyarakat sendiri yang harus menentukan masalah mereka. Bagaimana itu bisa dilakukan masyarakat, adalah tugas pengabdi atau organizer untuk memfasilitasi dialog, sampai masyarakat memahami masalah mereka sendiri. Jika organizer semula mendekati masyarakat dengan memilih kelompok sosial sendiri yang mereka senangi, biasanya akan membawa bias. Organiser akan bertanya masalah sosial pada orang pandai dan terdidik, berarti itu bias kesadaran. Atau bertanya kepada pejabat desa, itu bias jabatan. Atau bertanya pada penerima program, itu bias program. Pengorganisasian masyarakat dengan penuh bias ini menjadi berpotensi gagal.
Bias-bias ini akan menutupi persoalan yang sesungguhnya: kemiskinan, kelemahan, ketakberdayaan. Supaya tidak bias, maka organizer harus mendekati dan hidup bersama orang yang paling miskin, paling rentan, paling tak berdaya, dan paling lemah. Pendekatan itu akan memudahkan organizer memahami masalah kemiskinan, di sisi lain akan terjadi dialog supaya orang miskin mampu mengungkapkan sendiri apa yang mereka alami, mereka rasakan, mereka resahkan, dan mereka harapkan. Sebab, kemiskinan pada dasarnya adalah tidak kelihatan (unseen), yang terlihat adalah respon orang atas kemiskinan.

Jika telah terjadi pertaubatan metodologis melalui pembalikan kesadaran dan pendekatan seperti di atas, langkah berikutnya adalah mengelola kuasa (power) untuk mengubah nasip secara partisipatif. Organizer bekerja untuk menyelesaikan kemiskinan tidak hanya bersama orang miskin, namun juga dengan orang yang punya kuasa: jabatan, uang, kedudukan kultural, keilmuan dan lain-lain. Organizer membaca dialog antara pihak paling miskin dengan pihak paling berkuasa, maka yang akan terjadi adalah pembalikan sifat manusia: dari serakah menjadi berbagi, dari menutup diri menjadi berkorban (altruisme) untuk orang lain.
Asumsi tentang sifat watak manusia
Itu karena Chamber percaya bahwa sifat manusia ada dua, pertama serakah seperti hewan, kedua cinta kasih manusiawi yang mau berkorban tanpa pamrih. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk Pembangunan dan perubahan sosial dapat dilakukan seperti itu karena tiga alasan. Cara itu akan lebih efektif untuk menggerakkan perubahan dari dalam batin, atau cara itu juga akan membebaskan pikiran dari belenggu kepemilikan, atau cara itu juga menjadi pemenuhan kebutuhan dan kekosongan jiwa manusia.

Membaca metode Chamber terasa oleh saya begitu emosional, rasional dan spiritual sekaligus. Metode ini juga disebut metode pertaubatan sosial. Saya merasa akrab dengan metode ini, karena apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Wangsakerta Cirebon hampir semua membenarkan tesis Chamber. Bekerja dengan kelompok sosial paling disingkirkan oleh pemerintah desa di wilayah cantilan, terpisah dari pusat kegiatan Pemerintah Desa, namanya Dusun Karangdawa. Para organizer Wangsakerta bekerja di dusun ini bersama masyarakat yang paling miskin, tidak punya harapan, pemalu, dan sangat menghindari orang kota. Mereka tidak mudah mengungkapkan perasaan dan pikirannya tentang nasip yang mereka alami, kemiskinan. Saya sering menyebutnya kaum sub-altern, seperti yang Gayatri Spivak kenalkan.
Namun kekuatan utama Wangsakerta adalah mereka, terutama kelompok anak-anak dan ibu-ibu. Apa yang disinggung Chamber bekerja dengan orang luar sebagai bentuk empowerless, atau tidak mengedepankan kekuatan diri organizer sebagai orang luar, atau bunuh diri kelas, atau sharing kekuatan juga sangat terasa. Dampak respon positif yang mengubah pemegang kuasa untuk empati terhadap yang paling lemah muncul secara tak terduga. Dua Camat dari kecamatan Tengah Tani dan Kecamatan Mundu bergabung dan berkomitmen untuk melakukan penguatan desa-desa. Orang-orang kota menyedekahkan sebagian rejeki mereka untuk mendukung pekerjaan kami. Dan seterusnya…
Penutup
Dakwah sebagai upaya perubahan individu dan masyarakat memerlukan banyak sekali alat, perangkat, pengetahuan, skill, pendekatan dan berbagai instrumen yang lain. Metodologi menjadi sangat penting untuk memahami masyarakat, baik masyarakat modern maupun tradisional, dengan Langkah-langkah yang partisipatif di satu sisi, dan bertujuan kebaikan (ad-da’watu ilal khair) di sisi lain. Pemikiran Chambers memberi kontribusi untuk langkah-langkah metodologi dakwah yang sesuai dengan masyarakat modern sebagai korban dari proyek Pembangunan yang bersifat kapitalistik.
Refference:
Cambers, Robert. 1993. Participatory Rural Appraisal, in Hudson, Norman & Cheatle, Rodney. Working With Farmers for Better Land Husbandry. Intermediate Technology Publications in association with World Association of Soil and Water Conservation.
Cambers, Robert. 1994. Paradigm Shift and The Practice of Particpatory Research and Development. Inatitute of Development Studies.
Cambers, Robert. 2004. Ideas for Development: Reflecting Forwards. Sussex: Institute of Development Studies.